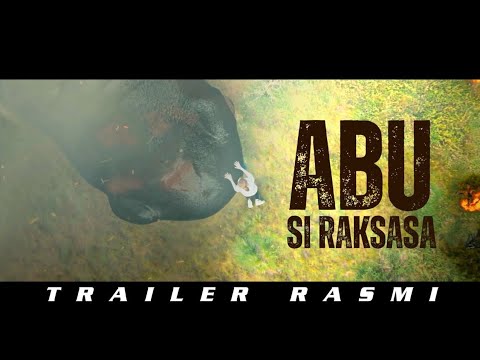oleh: zizi hashim
Sejujurnya, ketika mendengar judulnya pertama kali, saya sempat tersenyum sinis. Kaiju di Malaysia? Seekor cicak salamander jadi raksasa? Namun, sebaik sahaja duduk di pawagam, segala keraguan itu perlahan-lahan runtuh. Ada keberanian yang jarang kita temui di layar tempatan. Ada semangat yang menolak untuk hanya meniru, tetapi berusaha memahat identiti sendiri. Abu Si Raksasa adalah sebuah naskhah yang menolak dilihat sekadar tontonan, sebaliknya mahu menjadi cermin besar yang memantulkan wajah alam yang sedang kita abaikan.
Yang menjadikan filem ini istimewa adalah proses tercetus kelahirannya. Zamin Fakry, selaku penerbit, tidak mencari sensasi murah atau meniru formula luar. Ilhamnya datang dari sesi diskusi bersama Profesor Dr Hezri Adnan, seorang ahli akademik alam sekitar. Dari ruang perbualan intelektual itu lahirlah gagasan besar: mencipta hiburan yang bukan kosong, tetapi terikat dengan isu bumi yang semakin tenat. Abu dicipta sebagai perantara, seekor cicak kecil yang membesar menjadi raksasa bukan kerana keinginannya, tetapi kerana kerakusan manusia.


Sebagai penonton, saya hargai niat tulus filem ini. Bayangkan, daripada percakapan ilmiah, tercetus keberanian untuk melahirkan filem Kaiju pertama Malaysia. Bukankah itu bukti bahawa seni dan ilmu boleh berpaut erat, lalu melahirkan sesuatu yang berharga? Plotnya berpusat pada Zaara (dilakonkan Sophia Al-Barakbah), seorang gadis yang membela cicak salamander bernama Abu. Sewaktu Abu terlepas ke empangan yang sudah tercemar dengan bahan kimia daripada produk ROXCCID, tubuh kecilnya bermutasi menjadi gergasi. Dari titik inilah segalanya berubah.
Namun, Zaara menolak untuk melihat Abu sebagai raksasa menakutkan. Baginya, Abu tetap makhluk kecil yang pernah menemaninya. Bersama dua sahabatnya, Sofiyan (Jaa Suzuran) dan Zidan (Zalif Sidek), Zaara cuba mempertahankan Abu daripada operasi ketenteraan yang diketuai Kolonel Zamrose dan Kapten Fayyad. Di sinilah konflik utama mencengkam: negara melihat ancaman, tetapi hati seorang gadis melihat kesetiaan. Filem ini membuat saya bergelut dengan emosi antara logika yang menuntut perlindungan orang ramai, dan kasih yang menolak untuk mengkhianati sahabat.


Abu, pada akhirnya, adalah metafora tentang segala yang kita cintai tetapi perlahan-lahan dimusnahkan oleh tangan manusia sendiri. Keberanian produksi dengan bajet sekitar RM2 juta (jumlah yang kecil bagi sebuah filem raksasa) wajar diberi kredit justeru M Toons Media tetap nekad. CGI dan VFX menjadi tunjang, dengan hampir 40 peratus visual bergantung pada teknologi. Ramdan Che Hassan, pengarah dan penulis skrip, jujur mengakui cabarannya.
Namun bukannya mengeluh, dia memilih untuk mengangkat cicak salamander sebagai raksasa kerana keunikan spesis itu sendiri: amfibia dua alam, jinak, malah kadangkala dipelihara. Pemilihan ini membuat Abu lebih dekat dengan penonton, kerana ia lahir dari dunia nyata kita. Saya juga suka dengan keberanian mereka memilih lokasi seperti Tasik Tadom, Kajang, Banting dan Sungai Buaya. Lokasi-lokasi ini memberi sentuhan tempatan yang jujur, menjadikan naratif terasa milik kita, bukan sekadar tiruan Jepun atau Hollywood.


Keintiman filem ini juga disokong barisan pelakon yang menarik. Sophia Al-Barakbah membawa kelembutan dan tekad sebagai Zaara. Jaa Suzuran dan Zalif Sidek menambah warna sebagai sahabat yang setia. Afieq Shazwan menyalurkan aura ketegasan sebagai Kapten Fayyad, manakala Azhar Sulaiman dan Maria Farida memberi lapisan dramatik. Nama-nama lain seperti Adam Shahz, Samarinna Tolhip, Azri Iskandar, Along Eyzendy hingga Daddy Rock menjadikan ensemble ini lebih meriah. Dan ya, kemunculan khas Dato Rizal Mansor serta Ayahanda Rani Kulop menjadi buah mulut di kalangan penonton.
Usai menontonnya, saya melihat Abu ibarat cermin kepada dunia yang kita huni hari ini. Makhluk yang tidak pernah meminta untuk menjadi raksasa, tetapi terpaksa menanggung akibat dek pencemaran. Bukankah bumi kita juga sedang menjadi “Abu”, membesar dalam luka yang kita sendiri tabur? Saya melihat filem ini sebagai tanda mula, bukan penamat. Ia barangkali belum sempurna, tetapi keberanian mencuba sesuatu yang asing sudah cukup membuktikan bahawa sinema Malaysia masih hidup, masih berani.


Jika Abu Si Raksasa berjaya mencuri hati penonton, maka pintu untuk lebih banyak filem sains fiksyen tempatan akan terbuka lebar. Bagi saya, filem ini bukan hanya menandai kelahiran Kaiju pertama Malaysia. Ia adalah peringatan halus bahawa seni mampu menjadi suara alam. Dan setiap kali saya teringat wajah Zaara memeluk Abu, saya tahu kasih dan kehilangan itu tidak hanya berlaku di layar, tetapi juga sedang kita alami di dunia nyata.
Tarikh tayangan rasmi pada 11 September 2025 sudah terukir dalam kalendar pawagam Malaysia. Sebagai filem Kaiju pertama, ia membawa ekspektasi besar. Meskipun ada kelemahan, seperti CGI yang sesekali terasa belum matang, atau adegan peluru berpandu yang kurang logik kerana terlalu dekat dengan orang awam, semangat filem ini terlalu tulus untuk dipandang remeh.
Kadang kala, penonton terlalu selesa menonton genre yang sama berulang kali. Terlalu banyak filem seram, komedi, romantik sehingga terlupa bahawa sinema juga ruang untuk bereksperimentasi dan bermimpi lebih jauh. Abu Si Raksasa hadir tepat untuk menggoncang kebiasaan itu. Jadi, marilah kita beri peluang. Biarkan diri kita keluar dari zon selesa dan menyokong karya yang berani ini. Saksikan Abu Si Raksasa sebagai tanda permulaan bahawa sinema tempatan masih hidup, masih berani, dan masih punya mimpi besar.